Tempat: One Cafe, Kuala Lumpur
Masa: 3PM – 11PM
Tarikh: 27hb Februari 2010, Sabtu
Tiket: Pre Sale, RM25 at door, RM35
Oxygen Media, Frinjan & Envelove dengan sokongan My Future Foundation & IKD dengan rasa rendah diri mempersembahkan kepada audien Malaysia band yang sering digelar band ’sospol’ (sosial politik) kerana lirik-lirik mereka yang mengandungi elemen kritik sosial politik yang sarat dengan isi.
Melalui lagu-lagu pop yang enak didengar, lirik-lirik yang puitis dan dalam lebih mudah dihadam.
Kesan akibat pemanasan global bukan lagi omongan kosong sebaliknya realiti nyata yang sedang kita hadapi semua.
Begitu halnya juga dengan kebebasan baik dari segi politik, media dan pastinya muzik yang sering diancam dengan pelbagai alasan, dari moral hinggalah kepada ketenteraman awam.
Ayuh berhibur dan menyelami di sebalik bait lirik untuk kita fikir-fikir dan hadam-hadam dengan terbuka tanpa paksaan.
Turut akan beraksi ialah band tempatan yang turut sama mendokong iaitu Nao, Couple, Deepset, Dum Dum Tak, Free Love dan Bit the Medusa (mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia)
Istimewa!
Eksklusif! Diskustik bersama Efek Rumah Kaca
http://www.facebook.com/event.php?eid=185863678062
Tempat: Annexe Gallery, Kuala Lumpur
Masa: 8PM – 11PM
Tarikh: 26hb Februari 2010, Jumaat
Tiket: Percuma
Eksklusif! Diskustik Efek Rumah Kaca, acara ini merupakan kombinasi nyanyian lagu secara akustik dan diikuti dengan diskusi santai setelahnya. Efek Rumah Kaca dan juga Couple tidak akan menggurui sebaliknya akan berkongsi, bertukar dan berbahas; dari isu muzik, alam sekitar, kebebasan, demokrasi, korupsi, nasionalisme dan hak asasi manusia.
Maklumat Tiket
tiket ‘Konsert Efek Rumah Kaca’ akan mula dijual 26hb Disember
Pre Sale ticket RM25
At door RM35
Dengan membeli tiket pre sale, CD ERK album ‘Kamar Gelap’ dapat dibeli dengan harga RM25. Stok terhad! Harga asal RM30
Nak beli kat mana?
-emel ke oxygenmedia22@gmail.com dan ikut arahan selanjutnya
-dan di booth Oxygen Media/Frinjan di acara-acara yang bertebaran
-Rock The World 26hb Disember
-Pekan Frinjan 7.0
Kuala Lumpur
Rumah Frinjan
22 Lorong Rahim Kajai 13 Taman Tun Dr. Ismail 60000 KL
Zul: 019-308 3804
Dolls Store
79 Basement , Jln Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur ,Wilayah Persekutuan
http://www.myspace.com/dolls_store
Papakerma
http://www.papakerma.com/
Selangor
Badger Malaysia
18-M,Jalan SS21/58,
Damansara Utama, PJ
Selangor
03-7729 3005
Perak
Envelove Distro, Ipoh
No.11A, Persiaran Greentown 6, Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, Perak
envelovedistro@yahoo.com
Amir: 012-517 5646
Kudean: 017-461 2094
http://www.facebook.com/inbox/?tid=1225627168922#/envelovedistro?ref=ts
Johor
Embrace Studio
No 14-02 Jalan Sri Perkasa 2/22
Taman Tampoi Utama
81200 Johor Bahru, Johor
Diqin: 013 705 6243
Zaidee: 019-723 9329
Melaka
CHTQ STORE
No E 023,Jalan Merdeka
Dataran Pahlawan Megamall
75000,Bandar Hilir, Melaka
http://www.myspace.com/chantq
http://chantqshirt.blogspot.com/
Kelantan
Kedai Hitam Putih
Lot RF40, Aras 2
Medan Usahawan
Depan Stadium Sultan Muhammad
15000 Kota Bharu, Kelantan
http://thekedaihitamputih.blogspot.com/
Zaidi: 012 384 0415
Kedua-dua acara ini berlangsung sempena Festival Hak Asasi Manusia 2.0: Muzik Berserta Demokrasi dan Pengembangan Sosial yang berlangusng dari 26hb – 28hb Februari 2010
http://www.facebook.com/search/?q=frinjan&init=quick#/event.php?eid=216402600911&index=1
Muzik bukan maksiat!
Nak bertanya, juga oxygenmedia22@gmail.com atau Zul 019-308 3804
Efek Rumah Kaca Live in Kuala Lumpur 2010
Exclusive! Diskustik with Efek Rumah Kaca
http://www.facebook.com/event.php?eid=185863678062
Venue: Annexe Gallery, Kuala Lumpur
Time: 8PM – 11PM
Date: 26th February 2010, Friday
Admission: Free
Combination of acoustic singing and informal discussion with every members of the band Efek Rumah Kaca from music, global warming, human rights, democracy, freedom, music, nationalism, corruption. Not to be missed, Couple will join them.
Konsert Eco-Freedom: Efek Rumah Kaca Live in Kuala Lumpur
http://www.facebook.com/search/?q=frinjan&init=quick#/event.php?eid=206638468102&index=1
Venue: One Cafe, Kuala Lumpur
Time: 3PM – 11PM
Date: 27th February 2010, Saturday
Oxygen Media, Frinjan and Envelove Distro with the support of My Future Foundation would like to offer you a deal you certainly won’t refuse. Introducing the indie band Efek Rumah Kaca of Jakarta fame, a band renowned for their socio-political or ‘sospol’ approach of addressing social issues, non-partisan politics as well as environmental issues through sweet pop melody and easy to swallow poetic lyrics, thanks to Cholil, the band’s frontman.
Global warming effect is no longer empty talks but it is now a reality presented upon us challenging the very existence of us indeed.
Freedom of varying form suffers similar fate. Political freedom, media and communication freedom as well as music freedom are usually subjected to aggression on the grounds of morality, public order and many more.
On the lighter notes, let’s give our ear a treat of subtle and melodious aural assault and immerse your mind into the depth of the lyrics at your own pace. For you are not required to subscribe to the dogma. But if you do, you’ve certainly contribute something towards a better Earth for everyone.
Not to be missed! Accompanying local acts of Nao, Couple, Deepset, Dum Dum Tak, Nao, Free Love and Bit the Medusa.
Tickets.
Access tickets to ‘Konsert Efek Rumah Kaca’ will be available from 26th December 2009 onwards at selected outlets/agents.
Pre-sale Ticket RM25
Online Purchase RM50 + ERK latest EP of “Kamar Gelap” + freebies (limited)
At Door RM35
Pre-sale purchase, entitles you to grab ERK’s Efek Rumah Kaca and Kamar Gelap at RM25 only. RM5 reduced from original price of RM30.
Where can I get one?
Simple. Just send me an email at oxygenmedia22@gmail.com and follow the instructions carefully.
Or get yourselves passes from the appointed sales agents nationwide. Please refer to the Malay version as above.
Both events is part of Festival Hak Asasi Manusia 2.0: Muzik Berserta Demokrasi dan Pengembangan Sosial which will be held from 26th – 28th February 2010
http://www.facebook.com/search/?q=frinjan&init=quick#/event.php?eid=216402600911&index=1
Music is never a vice!
Feel free to drop an email to oxygenmedia22@gmail.com for inquiries or simply call me at 019-308 3804 (Zul)
Thank you!
Tentang band Efek Rumah Kaca
EFEK RUMAH KACA
The Best Cutting Edge 2008 – MTV Indonesia
Rookie Of The Year 2008- Rolling Stone Indonesia
Listening to Efek Rumah Kaca (ERK), an indie rock band from Jakarta, Indonesia, is like reading a newspaper since the band serves various themes on their songs.
ERK talks about consumerism on “Belanja Terus Sampai Mati”, photography on “Kamar Gelap”, politics on “Jalang”, “Di Udara”, and “Jangan Bakar Buku”, environment on “Efek Rumah Kaca” and ” Hujan Jangan Marah”, psychology on “Melankolia” and “Insomnia”, music industry on “Cinta Melulu”, and many more. Cholil (vocal/guitar) and Adrian (bass) write the lyrics like photographers capturing/documenting any daily life moments.
Formed in 2001, Efek Rumah Kaca is musically influenced by many great musicians/bands from different genres and era; Jon Anderson, Sting and The Police, The Smiths, Radiohead, The Smashing Pumpkins, and many more.
Anyone will get “theatre of mind experience” listening to ERK’s songs although not understanding the all Indonesian language lyrics. You will embrace the loneliness in “Lagu Kesepian” (Loneliness Song), or feeling the December month after rain beauty in “Desember” (December). The notes and precise sound choosing will take you there.
After several name changes, Efek Rumah Kaca released the self titled debut album “Efek Rumah Kaca” (Paviliun Records, 2007) which immediately drew positive response from various medias, music critics, internet bloggers, to music lovers.
“Cinta Melulu”, a satire of Indonesian music industry which is dominated by sappy love songs with stereotype music and lyric approach, became big hit in Indonesia. It brought ERK on the road, touring to cities in Indonesia and achieved various awards. “Cinta Melulu” was granted “Best Indonesian Song of 2008″ by a prestigious radio in Indonesia. Even the creativity of Efek Rumah Kaca songs overthrown pop music stagnancy which made Efek Rumah Kaca being claimed by media as “Indonesian music saver”.
December 2008 ERK released their second album, “Kamar Gelap”. In two weeks only, in national circulation, this album has been sold more than 3000 copies.
Efek Rumah Kaca has been loved by various circles. From “indie kids” to literature lovers. From visual artists to activists. From lecturers to junior high scoll students. In early 2009, Efek Rumah Kaca has even become the permanent writer for politic column in KOMPAS, biggest national newspaper in Indonesia.
Efek Rumah Kaca are Cholil (vocal/ guitar), Adrian (bass, background vocal), and Akbar (drums/ background vocal)
Discography:
“Melankolia” (Paviliun Do Re Mi/ compilation/ Paviliun Records/ 2006) “Di Udara” (Todays of Yesterdays/ compilation/ BadSectors Records/ 2006) “Efek Rumah Kaca” (full album/ Paviliun Records/ 2007) “Jatuh Cinta Itu Biasa Saja” (Valentine’s Love Songs/ compilation/ Hai Magazine/ 2008) “Banyak Asap di Sana” (Make Fair Trade/ compilation/ Kawanku Magazine/ 2008) “Hujan Jangan Marah” (Siaga Bencana/ compilation/ Electrified Records/ 2008) “Kamar Gelap” (full album/ Aksara Records/ 2008)
Achievments:
Sharing stage with Japan’s post rock/ ambience/experimental band Mono’s Jakarta show Opening act for Sweden’s electropop band Radio Dept’s Bandung show Opening act for Whitest Boy Alive and DJ Aoki’s Jakarta Show Nominated for “The Best Alternative” at Indonesia’s prestigious Anugerah Musik Indonesia Award 2008 Awarded “The Best Cutting Edge Band 2008” by MTV Indonesia Awarded “Rookie Of The Year 2008” by Rolling Stone Indonesia Awarded “Class Music Heroes 2008” by Class Mild
“… Siapa saja bisa mudah terpikat oleh irama riang dan riff gitar psychedelic rock yang menggemaskan pada “Kenakalan Remaja di Era Informatika”, termasuk pengguna kamera ponsel tak bertanggung jawab yang disindir di lagu ini…”- Rolling Stone Indonesia Edisi 44, Desember 2008.












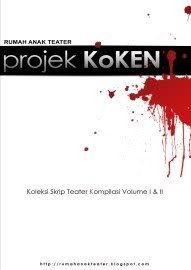


.jpg)




